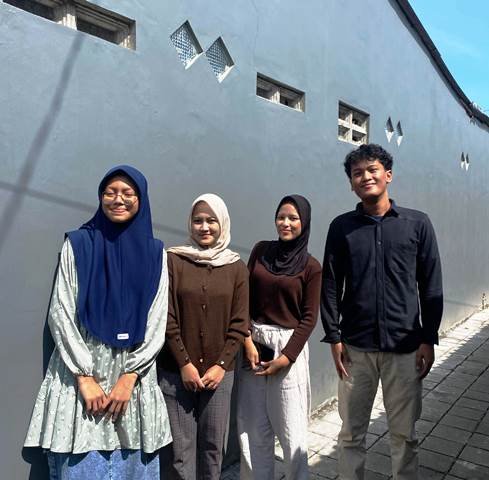Oleh: Tim Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB Unnes
PADA lini masa media sosial, tagar #KaburAjaDulu mendadak menjelma menjadi semacam manifesto virtual. Bukan sekadar guyonan belaka, ungkapan ini menyimpan keresahan kolektif: kekecewaan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keadilan yang dirasa stagnan di tanah air. Bagi banyak anak muda, tagar ini bukan soal pelarian, melainkan tentang harapan-harapan akan hidup yang lebih layak di luar batas negara bernama Indonesia.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada rakyat menjadi latar belakang utama munculnya tren ini. Di tengah segala keterbatasan, muncul gelombang pemuda-pemudi yang mulai melirik peluang di negeri orang menempuh studi, membangun karier, atau sekadar mencari napas yang lebih lega.
Melalui #KaburAjaDulu, warganet saling berbagi informasi tentang beasiswa, peluang kerja, pelatihan bahasa asing, hingga kisah pahit-manis hidup di luar negeri. Bukan semata ajakan kabur, melainkan sebuah bentuk perlawanan terhadap rasa frustasi yang kian menumpuk.
Fenomena ini bukan tanpa data. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pemerintah menargetkan penempatan 425.000 pekerja migran pada 2025, naik drastis dari 297.000 tahun sebelumnya. Negara-negara seperti Jepang, Arab Saudi, dan Taiwan tengah membuka pintu lebar untuk tenaga kerja luar, termasuk dari Indonesia. Namun, dari total kebutuhan 1,3 juta tenaga kerja global, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 20 persen. Artinya, peluang besar ada di depan, tapi kita belum cukup siap.
Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi nasional sangat signifikan. Remitansi atau kiriman uang dari luar negeri diperkirakan mencapai Rp250 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar negara.
Dalam kacamata akademik, tren ini relevan dengan Teori Sistem Dunia (Massey) dan Teori Modal Sosial (Castles & Miller). Migrasi terjadi karena ketimpangan ekonomi, tapi diperkuat oleh jaringan sosial yang menjembatani antara negara asal dan tujuan. Dan di era digital, jejaring ini berkembang pesat. Media sosial kini berperan bukan hanya sebagai wadah curhat, tetapi juga alat navigasi hidup di luar negeri.
Namun tak semua cerita migrasi berakhir manis. Realita di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia masih menempati sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Rendahnya keterampilan menjadi batu sandungan utama. Di sisi lain, praktik percaloan, penempatan ilegal, dan lowongan kerja fiktif masih menghantui, bahkan kini bermigrasi ke ranah digital.
Sepanjang Februari 2025, pengaduan terhadap pekerja migran melonjak hingga 124,69 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Permasalahan klasik seperti gaji tak dibayar, pekerjaan tidak sesuai kontrak, hingga deportasi masih menjadi luka lama yang terus menganga.
Menyadari potensi sekaligus tantangan ini, pemerintah mulai menyiapkan strategi: peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan sertifikasi keterampilan. Skema kerja sama Indonesia-Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW) menjadi salah satu contoh nyata upaya membuka akses ke sektor formal di luar negeri.
Pada akhirnya, tagar #KaburAjaDulu bukan semata ajakan kabur, tapi refleksi dari generasi yang merasa kehilangan ruang tumbuh di negerinya sendiri. Mereka tak sedang lari, mereka mencari. Dan jika negeri ini ingin mereka kembali, maka sudah saatnya kita menjawab keresahan mereka, bukan menertawakannya.
Penulis:
- Resty Nurlinda Aurellya
- Sumayyah
- Febriana Amaliah Putri
- Rakha Mukti Rahardi. Jatengdaily.com-st